Kemiskinan
masih menjadi salah satu penyakit kronis di Negeri ini yang masih belum bisa
disembuhkan. Hampir 70 Tahun Indonesia merdeka, kemiskinan masih tetap
menggerogoti Bangsa ini. Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk miskin baik
di Desa maupun di Kota dari tahun ke tahun semakin menurun. Pada Tahun 1970,
jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 70 Juta jiwa, sedangkan pada Tahun
2013 sekitar 29 Juta jiwa. dari data ini dapat kita lihat bahwa kemiskinan di Indonesia
memang sudah menurun.
Dari berbagai
macam teori tantang kemiskinan, permberdayaan adalah salah satu teori yang dianggap
paling mutakhir untuk menyelesaikan masalah kemiskinan (Syakrani,2009). Menurut
Ife (2002), pemberdayaan adalah proses peningkatan daya (power) individu atau
kelompok yang tidak beruntung. Jadi, dengan pemberdayaan individu atau kelompok
yang tidak beruntung bisa menjadi beruntung atau yang miskin menjadi tidak
miskin.
Ada yang menarik dari pendapat Ife tersebut. Yang menarik adalah
pandangan Ife mengenai kemiskinan. Sedikit mengesampingkan pemberdayaan yang
diungkapkan oleh Ife, pandangan Ife tentang kemiskinan lebih menarik untuk
dibahas. Ife menyebut Orang-orang miskin sebagai orang yang tidak beruntung. Ini
dapat dilihat dari pengertian pemberdayaan menurutnya di atas.
Apa yang
dimaksud dengan ketidakberuntungan menurut Ife di atas? Apa kaitannya dengan
kemiskinan? Disini kita akan membahas
mengenai ketidakberuntungan dalam kemiskinan.
Secara sederhana,
konsep ketidakberuntungan bisa terwujud dalam berbagai bentuk. Kemiskinan atau
pemiskinan, marjinalisasi, deprivasi, dan ketidakadilan (Syakrani dan Syahrani,
2009). Secara teoritik, setidaknya ada tiga pandangan tentang ketidakberuntungan
sebagai isu sosial dalam kemiskinan, yakni pandangan individual, pandangan
kelembagaan, dan pandangan struktural.
|
Perspektif
|
Persepsi
Masalah
|
Sifat
Pandangan
|
Solusi
|
Individual
|
Patologi individu: fisik,
psikologis, moral atau karakter.
|
Blaming the Victim
|
Terapi, perlakuan medis, perubahan
perilaku, control, “pencucian moral”
|
Institusional
|
Patologi lembaga
(Bureaucratic pathology)
|
Blaming the Rescue
|
Reorganisasi, penambahan sumberdaya, diklat.
|
Struktural
|
Deprivasi atau
Diskriminasi
(kelas social, gender, power, dsb)
|
Blaming the system
|
Perubahan system (nilai aturan
main, mind-set kolektif)
|
Pandangan pertama, memahami ketidakberuntungan sebagai akibat dari
patologi personal atau individu. Sifat-sifat atau kondisi obyektif setiap
individu seperti malas, tidak terampil, tidak kreatif, kurang pengetahuan dan
sumberdaya dianggap sebagai determinan ketidakberuntungan. Pandangan ini
bersifat blaming the Victim, dan karena itu solusi yang ditawarkan
difokuskan pada pembenahan patologi atau kekurangan secara individual, meskipun
dalam pelaksanaannya didekati secara kolektif. Bayak program sosial dirancang
dengan basis teoritik blaming the victim, seperti program kompensasi BLT, bantuan
modal, dan pelatihan-pelatihan keterampilan.
Pandangan kedua, memfokuskan
pandangannya pada kinerja lembaga penanggungjawab masalah sosial. Ketidakberuntungan
yang dialamai penduduk dalam pendangan ini dipahami sebagai akibat sampingan
ketidakmampuan lembaga tersebut menunaikan tanggungjawabnya. Pandangan ini
bersifat blaming the rescuer, karena itu jalan keluar yang ditawarkan
bersifat kelembagaan, seperti pengembagan kapasitas, pengembangan organisasi,
penambahan sumberdaya, pendidikan dan pelatihan manajemen pembangunan sosial. Dalam
beberapa kasus program sosial, juga dikaitkan dengan pembenahan kelembagaan. Tapi
masalahnya adalah program yang digelar, seperti diklat dan perampingan
borokrasi tidak dirancang dengan benar, sehingga pembenahan secara kelembagaan
ini seolah-olah berjalan sendiri-sendiri dan kehilangan pautannya dengan inti
masalah.
Pandangan ketiga, menganggap ketidakberuntungan
disebabkan oleh system dan norma sosial yang berlaku, yang dinilai
diskriminatif. Munculnya konsep kemiskinan struktural (deprivation atau
improverishment) bisa dipahami oleh konteks pandangan ini. Secara empirik,
jarang sekali program pembangunan sosial dirujukkan pada prespektif teoritik
ini. Akibatnya, potensi banyak program pembangunan sosial untuk memberdayakan
penduduk terhalangi oleh kurang pekanya penentu kebijakan dan perancang program
terhadap kendala struktural.
Dari
ketiga pandangan tentang ketidakberuntungan di atas, secara sederhana dapat
kita pahami mengenai konsep ketidakberuntungan. Dalam kaitannya dengan
kemiskinan, ketidakberuntungan diartikan sebagai sebab munculnya kemiskinan. Orang
miskin ada karena mereka tidak beruntung dalam menjani kehidupannya.
Kritik terhadap Ketiga pandangan Ketidakberuntungan
Awalnya,
jika kita menganggap sebuah kemiskinan muncul karena ketidakberuntungan adalah
sebuah pandangan yang agas sempit. Hal ini karena kita memaknai
ketidakberuntungan sebagai sebuah kondisi dimana manusia secara tidak sengaja
berada dalam kondisi yanglebih buruk dibandingkan yang lain. Artinya adalah
ketidakberuntungan yang dimaksud di awal adalah ketidaksengajaan terjebak dalam
sebuah kondisi yang buruk. Pandangan awal ini tentu akan sangan menyesatkan
jika dijadikan sebagai landasan dalam membedah persoalan kemiskinan.
Akan
tetapi setelah mengetahui ketiga pandangan tentaang ketidakberuntungan, tentu
kita sudah sedikit maju dalam mengetahui ketidakberuntungan apa yang dimaksud
dalam konteks kemiskinan. Pandangan pertama
dari ketidakberuntungan bisa dikatakan seperti pandangan awal kita tentang
ketidakberuntungan, dimana manusia tidak beruntung karena kondisi
individualnya, entah itu fisik, mental, atau
sumber daya yang mereka miliki. Pandangan ini seakan-akan menyalahkan si
tidak beruntung karena kondisinya yang demikian. Akan tetapi pendangan
iniseakan-akan menghiraukan pertanyaan mengenai mengapa kondisi fisiknya
seperti itu? Mengapa psikologisnya seperti itu? Dan mengapa dia tidak memiliki
sumber daya? Pandangan ini akan kesulitan untuk mengaitkan pandangannya dengan
pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sehingga yang terjadi adalah rasa pesimisme
dari si tidak beruntung. Si tidak beruntung akan menganggap bahwa ketidak
beruntungannya adalah Takdir yang harus diterima. Dan si tidak beruntung akan
terus terjebak akan kondisinya yang serba kurang dengan menyalahkan Takdir
tersebut. Pandangan ini juga mengabaikan bahwa kondisii individu seseorang
dibentuk oleh lingkugan, terutama kondisi psikologis dan akses terhadap sumber
dayanya. Jadi, solusi yang ditawarkan dengan membenahi secara individu akan
menjadi sia-sia jika lingkungannya masih membuat kondisi si tidak beruntung
tetap berada dalam kondisi ketidakberuntungannya.
Memang
yang bertanggung jawab untuk mengetas kemiskinan yang dialami oleh masyarakat
adalah Pemerintah. Begitu pula dengan pandangan
kedua yang menganggap bahwa ketidakberuntugan terjadi akibat kegagalan
lembaga Pemerintah dalam membuat individu-individu Masyarakat menjadi
beruntung. Sehingga solusi yang ditawarkan hanya seputar pembenahan lembaga
Pemerintahan. Solusi yang seperti ini akan menjadi tidak berguna ketika
Pemerintah yang sudah dibenahi masih juga memiliki sifat yang semaunya sendiri
dan masih terjebak pada anggapan seperti pandangan pertama. Pandangan seperti
ini juga akan membuat keberuntungan yang dialami si tidak beruntung bersifat
sementara. Hal iin karena Pemerintah selaku penyelamat. Bukan si tidak
beruntung untuk membuat yang tidak beruntung menjadi beruntung.
Pada
pandangan ketiga bisa dikatakan
pandangan yang paling dipinggirkan ketika melakukan kajian tentang kemiskinan. Pandangan
ketiga yang “menyalahkan” sistem ketika terjadi ketidakberuntungan dipinggirkan
karena pandangan ini dianggap terlalu radikal. Hal ini dikarenakan mayoritas
masih menganggap bahwa individu adalah pusat dari kehidupan. Artinya adalah individulah
yang mempengaruhi lingkungan, bukan sebaliknya. Pandangan terhadap kedudukan individu
terhadap lingkungannya yang seperti inilah yang mengakibatkan pandangan ketiga
ini disingkirkan. Pandangan ketiga yang “menyalahkan” sistem, meletakkan individu
sebagai bagian dari lingkungan yang saling berinteraksi. Bukan individu yang
membentuk lingkungan, tetapi sebaliknya. Individu-individu akan dipengaruhi
oleh lingkungan tempatnya hidup. Jadi, beruntung atau tidak beruntungnya
seserorang tergantung dari lingkungan pembentuknya. Jika lingkungannya sangat
kapitalistik dan liberal, maka individu yang memiliki sumber daya lemah dan
sedikit akan tidak beruntung. Berbeda jika lingkungannya “sama rasa, sama rasa”
atau lingkungan yang sosialis, maka individu dengan sumber daya lemah dan
sedikitpun masih bisa beruntung. Kondisi sistem sosial yang demikianlah yang
dimaksud oleh pandangan ketiga sehingga
muncul istilah kemiskina struktural atau kemiskinan yang diciptakan oleh
struktur sosial yang ada. Begitulah sedikit wawasan tentang ketidakberuntungan
dalam konteks kemiskinan. Semoga bermanfaat….
MERDEKA !!!
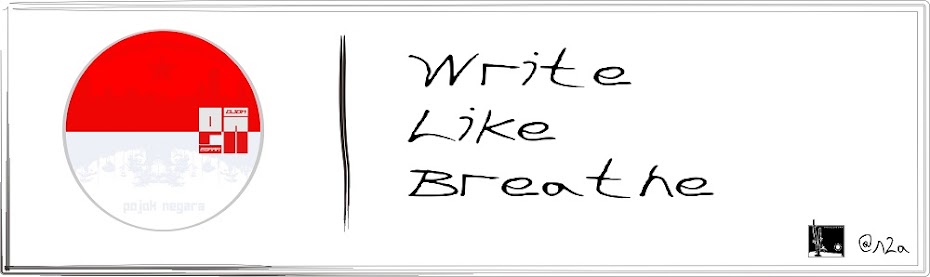
Tidak ada komentar:
Posting Komentar